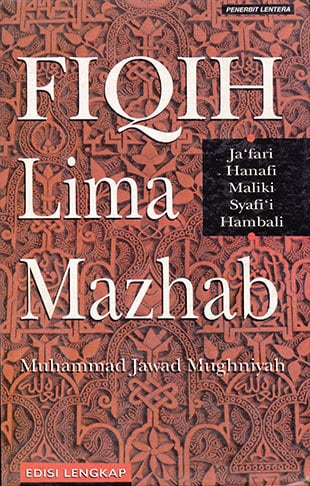BAB 13
QIBLAT
Semua ulama madzhab sepakat bahwa Ka‘bah itu adalah qiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang qiblat bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihatnya.
Ḥanafī, Ḥanbalī, Mālikī dan sebagian kelompok dari Imāmiyyah: Qiblatnya orang yang jauh adalah arah di mana letaknya Ka‘bah berada, bukan Ka‘bah itu sendiri.
Syāfi‘ī dan sebagian kelompok dari Imāmiyyah: Wajib menghadap Ka‘bah itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah Ka‘bah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadapinya ke arah tersebut. Tapi bila tidak, maka cukup dengan perkiraan saja. Yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukannya selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, qiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada Ka‘bah itu sendiri.
Orang Yang Tidak Mengetahui Qiblat
Orang yang tidak mengetahui qiblat, maka ia wajib menyelidiki, berusaha dan ber-ijtihād sampai yang mengetahuinya atau memperkirakan bahwa qiblat ada di satu arah tertentu. Tapi bila tetap tidak bisa mengetahuinya dan juga tidak dapat memperkirakan, maka menurut Empat madzhab dan sekelompok dari Imāmiyyah: Ia shalat ke mana saja yang disukainya dan sah shalatnya. Dan tidak wajib mengulanginya lagi, menurut Syāfi‘ī.
Sebagian besar Imāmiyyah: Ia harus shalat keempat arah sebagai rasa pantun dalam melaksanakan perintah shalat, sebab salah satunya pasti ada yang tepat. Tapi bila waktunya sudah sempit untuk mengulang ulang sampai 4 kali, atau tidak mampu untuk mendirikan salat keempat arah, maka cukup shalat pada sebagian arah yang ia mampu saja. (16)
Kalau ia sholat tidak mengarah qiblat, kemudian ia dapat mengetahui bahwa hal itu salah, maka menurut:
Imāmiyyah: Kalau kesalahannya itu diketahui ketika sedang shalat, dan ia miring (tidak mengarah) ke qiblat ke kanan atau ke kiri, maka ia harus melanjutkan shalat yang telah dilakukan, tetapi sisanya harus diluruskan ke arah qiblat. Kalau ia tahu bahwa ia shalat ke arah Timur, Barat, Utara atau justru membelakangi qiblat, maka batallah shalatnya dan ia harus mengulanginya lagi dari pertama. Bila ia mengetahui setelah selesai shalat, maka ia harus mengulangi lagi pada waktu itu, bukan di luar waktu itu.
Sebagian Imāmiyah: Tidak usah mengulangi lagi pada waktu tersebut dan tidak boleh di luarnya kalau ia meleset sedikit dari arah qiblat. Tapi kalau ia telah shalat pada arah Barat atau ke Timur, maka ia harus mengulanginya lagi pada (di dalam) waktu tersebut, bukan di luarnya. (Arah tersebut berlaku di tempat pengarang buku ini; tapi kalau di Indonesia, mungkin kalau menghadap ke Utara atau Selatan-Pent.). Dan bila nampak jelas bahwa ia membelakangi qiblat, maka ia harus mengulanginya lagi pada (di dalam) waktu tersebut maupun di luarnya.
Ḥanafī dan Ḥanbalī: Kalau ia berusaha dan ber-ijtihād untuk mencari arah qiblat, tetapi tidak ada satu arah pun dari beberapa arah yang lebih kuat untuk dijadikan patokan arah qiblat, maka ia boleh shalat menghadap ke mana saja, bila kemudian mengetahui bahwa ia salah, maka kalau dia masih di pertengahan, ia harus berubah ke arah yang diyakininya atau arah yang paling kuat. Tapi bila mengetahui bahwa ia salah setelah selesai shalat, maka sah shalatnya dan tidak diwajibkan mengulangi shalatnya.
Syāfi‘ī: Kalau ia tahu bahwa ia salah dengan cara yang meyakinkan, maka ia wajib mengulanginya lagi. Tapi bila hanya mengetahui dengan cara perkiraan saja, maka sah shalatnya, tidak ada bedanya, baik ketika sedang shalat maupun sesudahnya.
Sedangkan bagi orang yang tidak mau berusaha dan tidak mau ber-ijtihād, kemudian nampak bahwa ia telah shalat ke arah qiblat dan benar, maka shalatnya batal, menurut Mālikī dan Ḥanbalī.
Ḥanafī dan Imāmiyyah: Sah shalatnya kalau ia shalat tanpa ada keraguan dan ketika memulai shalat ia yakin bahwa ia menghadap ke arah qiblat, karena pada keadaan seperti itu ia telah melakukan sesuatu (perbuatan) yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka salah niatnya, begitulah pendapat Imāmiyyah.
Catatan: