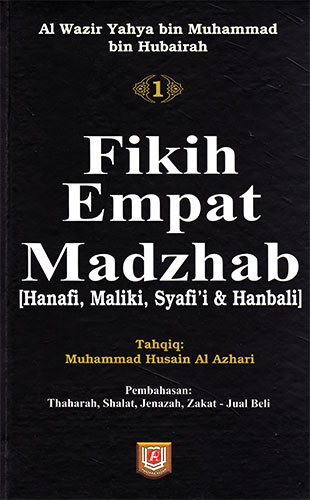Bab: Syarat Sahnya Shalat (361).
208. Mereka (Mālik, Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Ḥanbal, dan asy-Syāfi‘ī) sepakat bahwa sucinya tempat shalat merupakan salah satu kewajiban dan bahwa ia merupakan salah satu syarat sahnya shalat. (362).
[…..] (363)
209. Keempat Imām madzhab (Mālik, Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Ḥanbal, dan asy-Syāfi‘ī) sepakat bahwa menutup aurat dari pandangan hukumnya wajib dan bahwa ia merupakan syarat sahnya shalat. Kecuali Mālik yang mengatakan: “Hukumnya wajib dalam shalat tapi bukan syarat sahnya, hanya saja ia sangat dianjurkan.”
Di antara pengikut Mālik ada yang mengatakan: “Ia adalah syarat bila ingat dan mampu.” (364).
210. Mereka sepakat bahwa sucinya pakaian orang yang shalat merupakan syarat sahnya shalat. (365).
211. Mereka sepakat bahwa suci dari hadats merupakan syarat sahnya shalat.
212. Mereka sepakat bahwa sucinya badan dari najis merupakan syarat sahnya shalat…..
213. Mereka sepakat bahwa mengetahui masuknya waktu shalat atau munculnya dugaan kuat bahwa waktu shalat telah masuk merupakan syarat sahnya shalat. Kecuali Mālik yang mengatakan bahwa syarat sahnya shalat menurutnya adalah mengetahui masuknya waktu. Sedangkan dugaan kuat, menurutnya bukan syarat sahnya shalat.
214. Mereka sepakat bahwa menghadap qiblat merupakan syarat sahnya shalat, berdasarkan firman Allah s.w.t.:
وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ.
“Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.” (Qs. al-Baqarah [2]: 144).
Kecuali bagi yang berhalangan, yaitu dalam dua kondisi, saat perang dan saat takut yang berlebihan.
Shalat sunah di atas kendaraan dalam perjalanan panjang karena darurat dibolehkan, meskipun dia tetap disuruh menghadap ke arah qiblat, dan saat Takbirat-ul-Ihram dia disuruh menghadap ke arahnya semampunya. Apabila orang yang shalat berada di dekat Ka‘bah maka dia harus menghadap ke arahnya langsung, sedangkan bila posisinya dekat dengannya maka dia harus menghadap ke arahnya berdasarkan keyakinannya, sementara bila dia berada jauh darinya maka berdasarkan Ijtihad dan Taqlid atau berdasarkan informasi dari orang yang ahli.
215. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang wajib berijtihad yang tinggal di Makkah atau Madīnah yang tidak bisa melihat Ka‘bah secara langsung karena jaraknya yang tidak memungkinkan dan tidak ada yang memberi informasi kepadanya dengan akurat, apakah dia boleh berijtihad untuk menentukan arah qiblat?
Aḥmad berkata dalam riwayat yang masyhur darinya bahwa orang tersebut harus menghadap ke arah qiblat. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Khirāqī (366) Sementara dalam riwayat lain dia berkata: “Dia harus menghadap secara langsung.”
Diriwayatkan pula dari para pengikut Mālik dan asy-Syāfi‘ī seperti dua madzhab di atas. Sementara menurut pengikut Abū Ḥanīfah, orang tersebut harus menghadap ke Ka‘bah secara langsung. (367).
Manfaat dari perbedaan pendapat ini adalah (368), bahwa orang yang mengatakan bahwa orang yang shalat harus menghadap ke Ka‘bah secara langsung, dan bila dia melenceng sedikit saja maka shalatnya tidak sah. Sedangkan bagi yang mengataakan bahwa orang yang shalat cukup menghadap ke aranya maka shalatnya sah meskipun dia tidak menghadap ke arahnya secara tepat (melenceng sedikit). (369).
216. Mereka sepakat bahwa orang yang muqim (menetap) di suatu negeri tidak boleh menunaikan shalat sunah dengan menghadap selain qiblat, baik ketika sedang naik kendaraan maupun ketika jalan kaki. (370).
217. Mereka sepakat bahwa apabila posisi qiblat tidak jelas lalu seseorang berijtihad (untuk menentukan arah qiblat) dan benar maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya. (371).
218. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang shalat dengan menghadap ke arah tertentu (yang diduga arah qiblat) berdasarkan Ijtihad lalu ternyata Ijtihadnya salah maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya. Kecuali menurut salah satu dari dua pendapat Imām asy-Syāfi‘ī yang baru bahwa dia harus mengulang shalatnya.
Mālik berkata: “Apabila ternyata dia melenceng dari arah qiblat maka dia tidak perlu mengulang shalatnya.”
Sedangkan bila ternyata dia membelakangi qiblat maka ada dua pendapat darinya tentang masalah mengulangnya. (372).
219. Mereka sepakat bahwa boleh menunaikan shalat sunah di atas kendaraan, termasuk shalat sunah Rawātib dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan tersebut (onta dsb.) menghadap bila perjalanannya jauh. (373).
220. Mereka berbeda pendapat tentang perjalanan jarak dekat.
Asy-Syāfi‘ī dan Aḥmad berkata: “Hukumnya dibolehkan.”
Mālik berkata: “Tidak boleh kecuali dalam perjalanan jarak jauh.”
Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah, dalam hal ini ada dua riwayat.
Pertama, seperti madzhab Mālik.
Kedua, hukumnya dibolehkan di luar daerahnya meskipun dia tidak berniat melakukan perjalanan. (374).
221. Mereka berbeda pendapat, apakah boleh menunaikan shalat fardhu di atas kendaraan (onta dll.)?
Abū Ḥanīfah berkata: “Boleh pada saat berhalangan, seperti turunnya salju, sakit dan turun hujan, saat perang dan mencari musuh, dengan syarat kendaraan tersebut berhenti sampai shalat selesai.”
Asy-Syāfi‘ī berkata: “Tidak boleh menunaikan shalat fardhu dalam semua kondisi tersebut kecuali di atas tanah, kecuali ketika dalam kondisi sangat takut saat terjadi peperangan.”
Menurut Imām Aḥmad, dalam hal ini ada beberapa riwayat yang berbeda darinya. Diriwayatkan darinya bahwa shalat fardhu tidak boleh dilaksanakan di atas kendaraan kecuali saat kondisi perang dan mencari musuh. Sedangkan dalam selain dua kondisi ini maka shalat tetap dilakukan di atas tanah.
Diriwayatkan pula dari Aḥmad bahwa orang sakit boleh melaksanakannya. Ada pula riwayat darinya bahwa hukumnya tidak dibolehkan.
Abū Dāūd (375) juga meriwayatkan darinya bahwa boleh menunaikan shalat di atas kendaraan (onta dsb.) bila kondisi jalan berlumpur (endut) atau turun hujan atau turun salju.
Mālik berkata: “Shalat fardhu hanya boleh dilaksanakan di atas tanah, kecuali bila orang tersebut berstatus musafir yang khawatir bila dia turun maka temannya akan meninggalkannya. Juga saat kondisi perang, dalam kondisi ini dia boleh menunaikan shalat fardhu di atas kendaraannya.” (376).
222. Mereka sepakat bahwa shalat sunah di dalam Ka‘bah hukumnya sah.
223. Mereka berbeda pendapat tentang shalat fardhu di dalam Ka‘bah atau di atasnya.
Abū Ḥanīfah berkata: “Apabila di hadapan orang yang shalat ada sesuatu dari tandanya maka dibolehkan.”
Asy-Syāfi‘ī berkata: “Tidak sah shalat di atas Ka‘bah kecuali dengan menghadap tirai yang dibuat dari kapur batu atau tanah liat. Akan tetapi bila ia terbuat dari batu bata atau batu merah yang disusun maka hukumnya tidak boleh. Adapun bila tirai tersebut berbentuk kayu yang ditancapkan maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqahā’ Syāfi‘iyyah. Apabila seseorang shalat di dalam Ka‘bah dengan menghadap pintu maka hukumnya tidak dibolehkan kecuali bila di hadapannya ada ambang pintu yang bersambung langsung dengan bangunan Ka‘bah.
Aḥmad berkata: “Hukumnya tidak dibolehkan, baik di dalam Ka‘bah maupun di atasnya.”
Menurut Mālik, dalam hal ini ada dua riwayat. Riwayat yang masyhur adalah seperti madzahab Aḥmad, bahwa hukumnya tidak sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Ashbāgh.
‘Abd-ul-Wahhāb berkata: “Riwayat inilah yang masyhur di kalangan peneliti dari golongan imam-imam madzhab kami.”
Riwayat lain dari Mālik adalah bahwa hukumnya dibolehkan tapi makruh. (377).
224. Mereka berbeda pendapat tentang shalat di tanah hasil rampasan atau dengan memakai pakaian hasil rampasan.
Mereka mengatakan – selain Aḥmad – “Hukumnya sah meskipun hal tersebut buruk.”
Aḥmad berkata dalam riwayat yang masyhur darinya: “Shalatnya tidak sah.” (378).
Catatan: