02-2 Bab Waktu-waktu Shalat – Fikih Empat Madzhab
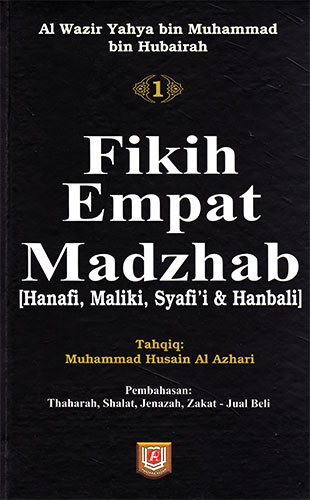
Fikih Empat Madzhab
(Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi‘i)
(Judul: Ijmā‘-ul-A’immat-il-Arba‘ati waikhtilāfihim).
Oleh: Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah
Penerjemah: Ali Mh.
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
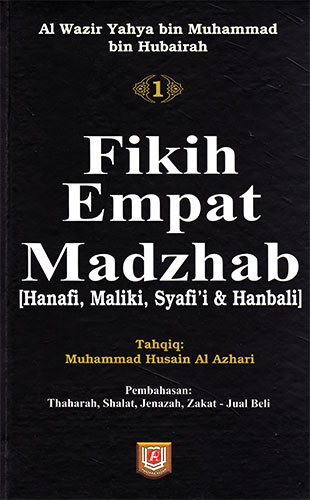
Fikih Empat Madzhab
(Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi‘i)
(Judul: Ijmā‘-ul-A’immat-il-Arba‘ati waikhtilāfihim).
Oleh: Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah
Penerjemah: Ali Mh.
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Bab: Waktu-waktu Shalāt (3081).
169. Keempat imam madzhab berbeda pendapat tentang waktu wajibnya shalāt.
Mālik, asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Shalāt wajib di awal waktu.”
Sebagian pengikut Abū Ḥanīfah berkata: “Shalāt wajib di akhir waktu.” (3092).
170. Mereka sepakat bahwa awal waktu Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir dan tidak boleh shalāt sebelum matahari tergelincir. (3103).
171. Mereka berbeda pendapat tentang akhir waktu shalāt Zhuhur.
Asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Akhir waktunya adalah bila bayang-bayang setiap sesuatu sama selain bayang-bayang seseorang saat matahari tergelincir, karena ia bisa panjang dan bisa pendek sesuai perbedaan waktu. Apabila bayang-bayang setiap sesuatu sama dan bertambah sedikit maka waktu Zhuhur telah habis dan masuk waktu ‘Ashar. Tambahan ini adalah awal waktu ‘Ashar. Apabila bayang-bayang setiap sesuatu sama dan bertambah sedikit maka ia adalah akhir waktu ‘Ashar.”
Menurut Abū Ḥanīfah, ada beberapa riwayat berbeda darinya. Diriwayatkan darinya pendapat yang sama dengan pendapat asy-Syāfi‘ī dan Aḥmad. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abū Yūsuf.
Ada pula riwayat lain darinya yang menyebutkan: “Apabila bayang-bayang setiap sesuatu sama dua kali lipat dengannya, maka ia adalah akhir waktu Zhuhur. Apabila lebih sedikit maka telah masuk waktu ‘Ashar.”
Ada pula riwayat darinya bahwa akhir waktunya adalah bila bayang-bayang setiap sesuatu sama dengannya, sedangkan awal waktu ‘Ashar adalah bila bayang-bayang setiap sesuatu dua kali lipat dengannya. Antara keduanya ada waktu yang bukan waktu keduanya. Akhir waktu ‘Ashar adalah sampai matahari menguning.
Mālik berkata: “Waktu Zhuhur Ikhtiyārī adalah sejak matahari tergelincir (ke arah barat) sampai bayang-bayang setiap sesuatu sama dengannya. Apabila bayang-bayang setiap sesuatu sama dengannya maka ia adalah akhir waktu Zhuhur Ikhtiyārī dan dengan sendirinya awal waktu ‘Ashar Ikhtiyārī telah masuk. Jadi waktu bagi keduanya bercampur antara keduanya. Apabila lebih sedikit maka waktu Zhuhur Ikhtiyārī telah habis dan masuk waktu ‘Ashar, dan waktunya terus berlangsung sampai bayang-bayang setiap sesuatu dua kali lipatnya, itulah akhir waktu ‘Ashar Ikhtiyārī. Kemudian waktunya berpindah dari Ikhtiyārī (dalam shalāt Zhuhur) ke waktu Dharūrī sampai matahari hampir tenggelam yang lamanya sekitar menunaikan shalāt lima raka‘at. Apabila matahari hampir tenggelam yang lamanya seperti menunaikan shalāt lima raka‘at yaitu 4 raka‘at shalāt Zhuhur dan satu raka‘at shalāt ‘Ashar, maka saat itu keduanya sama dalam hal darurat. Adapun perkataannya “apabila bayang-bayang setiap sesuatu sama denganya” berlaku pada semua orang saat matahari tergelincir. Sedangkan tentang perkataan Abū Ḥanīfah dan Mālik “apabila bayang-bayang setiap sesuatu sama dengannya atau dua kali lipatnya”, yang dimaksud adalah bahwa keduanya menganggapnya demikian sejak waktu berkurang dan bertambahnya, bukan dari asalnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari asy-Syāfi‘ī dan Aḥmad. Ini adalah kesepakatan mereka. (3114).
172. Mereka berbeda pendapat tentang waktu Maghrib.
Abū Ḥanīfah dan Aḥmad berkata: Maghrib memiliki dua waktu. Awal waktunya adalah ketika matahari terbenam, sedangkan akhir waktunya adalah ketika Syafaq (sinar merah) terbenam.”
Mālik dalam riwayat yang masyhur darinya dan asy-Syāfi‘ī dalam salah satu pendapatnya yang paling kuat dari dua pendapatnya mengatakan: “Maghrib memiliki satu waktu yang sempit yang akhirnya dikira-kira dengan selesainya waktu tersebut.”
Ada pula riwayat lain dari Mālik yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb bahwa ia memiliki dua waktu. (3125).
173. Mereka berbeda pendapat tentang Syafaq yang bila tenggelam menunjukkan masuknya waktu ‘Isyā’.
Mālik, asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Ia adalah sinar merah (pada matahari sebelum tenggelam).”
Abū Ḥanīfah berkata: “Ia adalah sinar putih.”
Ulama ahli bahasa cenderung pada pendapat pertama. Sementara menurut al-Khalīl (3136), al-Farrā’ (3147) dan Ibnu Duraid (3158), Syafaq adalah sinar merah.
Al-Farrā’ berkata: Aku mendengar sebagian orang ‘Arab mengatakan: “Dia memakai pakaian yang dicelup seperti Syafaq.”, maksudnya adalah warna merah. (3169).
174. Mereka berbeda pendapat tentang akhir waktu ‘Isyā’ Ikhtiyārī.
Mālik, asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad dalam riwayat yang masyhur dari mereka mengatakan: “Akhir waktu ‘Isyā’ Ikhtiyārī adalah sampai 1/3 malam.
Menurut pengikut Abū Ḥanīfah, terdapat beberapa riwayat yang berbeda dari mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan: “Akhir waktunya adalah sampai sebelum 1/3 malam.”
Ada pula yang mengatakan: “Akhir waktunya adalah sampai 1/3 malam.”
Ada pula yang mengatakan: “Akhir waktunya adalah sampai tengah malam.” Ini adalah pendapat lain Imām asy-Syāfi‘ī dan riwayat lain dari Aḥmad.
Mālik berkata: “Waktu Dharūrī shalāt Maghrib dan ‘Isyā’ adalah sampai sebelum terbit fajar yang lamanya sekitar 4 raka‘at, yaitu 3 raka‘at shalāt Maghrib dan 1 raka‘at shalāt ‘Isyā’.”
Ini adalah pendapat lain Imām asy-Syāfi‘ī dan riwayat lain dari Aḥmad.
Asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Waktu Dharūrī shalāt ‘Isyā’ adalah sampai terbit fajar. Barang siapa yang mendapati 1 raka‘at dari shalāt ‘Isyā’ sebelum fajar terbit maka dia telah mendapatinya.”
Abū Ḥanīfah berkata: “Waktu boleh adalah sampai fajar terbit.” (31710).
175. Mereka sepakat bahwa awal waktu shalāt Shubuḥ adalah terbitnya fajar kedua yang mengembang (di langit) yang tidak ada lagi kegelapan setelahnya, sedangkan akhir waktunya yang Ikhtiyārī adalah sampi suasana terang. (31811).
176. Mereka berbeda pendapat, apakah yang lebih utama mendahulukan shalāt Shubuḥ pada awal waktu?
Abū Ḥanīfah berkata: “Yang lebih utama adalah menunaikannya saat suasana terang, kecuali di Muzdalifah.”
Mālik, asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Yang lebih utama adalah menunaikannya saat suasana masih gelap.”
Ada pula riwayat dari Aḥmad yang mengatakan: “Yang jadi acuan adalah kondisi orang-orang yang shalāt. Bila suasana gelap memberatkan mereka maka menunaikannya saat suasana terang lebih utama. Sedangkan bila mereka telah berkumpul maka menunaikannya saat suasana gelap lebih utama.” (31912).
177. Mereka sepakat bahwa waktu Dharūrī adalah sampai matahari terbit. (32013).
178. Mereka sepakat bahwa yang lebih utama adalah menunda shalāt Zhuhur dari waktu bolehnya pada hari mendung. Kecuali asy-Syāfi‘ī yang mengatakan: “Apabila menurut dugaan kuatnya waktu Zhuhur telah masuk maka dia boleh menunaikannya tanpa menundanya.”
Diriwayatkan dari asy-Syāfi‘ī bahwa dia berkata: “Apabila langit mendung maka ditunggu kemunculan matahari. Bila ia telah terlihat maka shalāt harus segera dilaksanakan. Sedangkan bila ia belum terlihat maka shalāt Zhuhur ditunda sampai dia merasa bahwa dia menunaikannya pada akhir waktu. Dia harus berhati-hati dalam menundanya antara waktu tersebut sampai dikhawatirkan masuk waktu ‘Ashar. (32114).
179. Mereka sepakat bahwa yang lebih utama adalah menunda shalāt Zhuhur pada saat cuaca panas bila shalāt tersebut dilaksanakan di masjid yang biasa ditunaikan shalāt Jamā‘ah di dalamnya. Berbeda dengan sebagian pengikut Imām asy-Syāfi‘ī yang berpendapat bahwa hal tersebut hanya berlaku di negeri-negeri yang iklimnya panas saja, bukan di negeri lain yang iklimnya tidak panas. (32215).
180. Mereka sepakat bahwa disunnahkan menyegerakan shalāt Zhuhur pada musim dingin bila tidak ada mendung dan pada musim panas bila shalat tersebut tidak dilakukan di masjid yang biasa ditunaikan shalāt Jamā‘ah di dalamnya. Kecuali Mālik yang mengatakan: “Disunnahkan menunda shalāt sampai bayang-bayang sesuatu setinggi satu hasta bila shalāt tersebut dilaksanakan di masjid yang biasa ditunaikan shalāt Jamā‘ah di dalamnya.” (32316).
181. Mereka berbeda pendapat, manakah yang lebih utama dalam shalāt ‘Ashar, apakah menyegerakan atau menundanya pada semua waktu?
Abū Ḥanīfah berkata: “Menundanya lebih utama selama matahari belum menguning.”
Mālik, asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Mendahulukannya lebih utama.” (32417).
182. Mereka sepakat bahwa yang lebih utama adalah menunda shalāt ‘Isyā’. Kecuali asy-Syāfi‘ī yang mengatakan dalam salah satu dari dua pendapatnya bahwa menyegerakannya lebih utama. (32518).
183. Mereka berbeda pendapat tentang shalāt Wusthā.
Abū Ḥanīfah dan Aḥmad berkata: “Ia adalah shalāt ‘Ashar.”
Mālik dan asy-Syāfi‘ī dalam salah satu dari dua pendapatnya berkata: “Ia adalah shalāt Shubuḥ.”
Sedangkan menurut pendapat lain asy-Syāfi‘ī adalah bahwa ia shalāt ‘Ashar, dan inilah pendapat yang paling kuat. (32619).
184. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang menderita epilepsi.
Mālik dan asy-Syāfi‘ī berkata: “Bila epilepsi tersebut terjadi karena sebab yang diharamkan, seperti minum Khamer (miras) atau obat yang tidak dibutuhkan, maka kewajiban shalāt tidak gugur darinya dan dia wajib mengqadhā’nya. Sedangkan bila dia menderita epilepsi karena gila atau sakit atau sebab tertentu yang mubah maka dia tidak wajib mengqadhā’ shalāt selama masa epilepsi tersebut.
Abū Ḥanīfah berkata: “Apabila epilepsinya terjadi sehari semalam atau kurang dari itu maka hal tersebut tidak menghalangi wajibnya qadhā’. Sedangkan bila lebih dari itu maka dia tidak wajib mengqadhā’.”
Dalam hal ini Abū Ḥanīfah tidak membebakan sebab-sebab epilepsi tersebut.
Aḥmad berkata: “Epilepsi dengan seluruh sebabnya tidak menghalangi wajibnya Qadhā’.” (32720).
Catatan: