01-0 Kitab Thaharah – Fikih Empat Madzhab
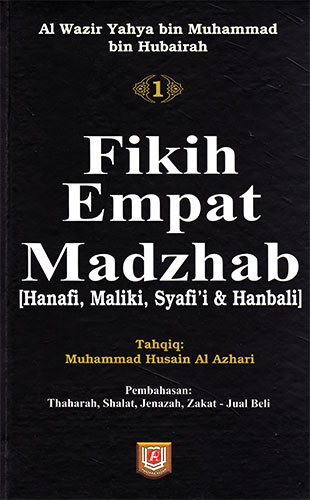
Fikih Empat Madzhab
(Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi‘i)
(Judul: Ijmā‘-ul-A’immat-il-Arba‘ati waikhtilāfihim).
Oleh: Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah
Penerjemah: Ali Mh.
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
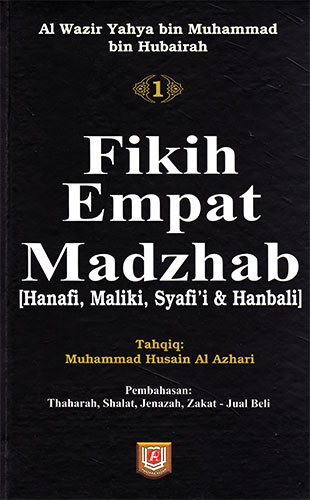
Fikih Empat Madzhab
(Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi‘i)
(Judul: Ijmā‘-ul-A’immat-il-Arba‘ati waikhtilāfihim).
Oleh: Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah
Penerjemah: Ali Mh.
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
KITĀB THAHĀRAH (571)
1. Keempat imam Madzhab (Mālik, Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Ḥanbal, dan asy-Syāfi‘ī) sepakat bahwa shalat tidak sah kecuali dengan Thahārah, bila ditemukan jalan untuk melakukan Thahārah. (582)
Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t.:
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَّرْضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
“Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, serta sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), lalu sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapai dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. al-Mā’idah [5]: 6).
2. Mereka juga sepakat bahwa fardhu wudhu’ ada empat, yaitu:
(a). Membasuh muka;
(b). Membasuh dua tangan sampai siku;
(c). Mengusap kepala; dan
(d). Membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. (593).
3. Mereka berbeda pendapat tentang yang lebih dari empat rukun di atas. Menurut Abū Ḥanīfah, hukumnya sunah atau mustahab, tidak fardhu (604). Sementara menurut asy-Syāfi‘ī dan Aḥmad, niat dan tertib merupakan fardhu wudhu’. (615).
Malik berpendapat: “Niat dan berturut-turut (Muwālāt) adalah fardhu wudhu’, sedangkan tertib bukan fardhu.” (626).
Ini yang diriwayatkan oleh Muḥammad bin ‘Abd-il-‘Azīz al-Warrāq al-Lakhamī dalam kitab al-Jam‘u wal-Khilāf. (637).
[Dan] (648) para ahli bahasa berkata: (659) Thahūr artinya adalah yang menjadikan suci sesuatu yang lain, sebagaimana dikatakan Qatūl.
Tsa‘lab berkata: (6610): “Thahūr adalah sesuatu yang dirinya suci lagi mensucikan yang lain.”
Definisi ini tidak ada yang menyelisihinya selain beberapa pengikut Abū Ḥanīfah. Mereka berkata: “Thahūr adalah sesuatu yang suci secara berlebihan.” (6711).
4. Mereka juga sepakat bahwa Thahārah wajib menggunakan air bagi siapa saja yang wajib menunaikan shalat ketika ada air. Bila tidak ada air maka gantinya adalah tanah yang suci. Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t.:
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا
“Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci) lalu basuhlah wajah dan tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. an-Nisā’ [4]: 43).
Juga firman-Nya:
وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu.” (QS. al-Anfāl [8]: 11) (6812).
Para ahli bahasa berkata: (6913) “Thahārah adalah membersihkan diri dari kotoran dan najis.”
5. Mereka juga sepakat bahwa apabila air berubah dari asalnya (bentuknya) karena sesuatu yang suci yang mendominasi bagian-bagiannya yang secara umum air tersebut tidak butuh terhadapnya maka tidak boleh berwudhu’ dengannya (7014). Kecuali Abū Ḥanīfah yang membolekan berwudhu’ dengan air yang berubah karena bercampur dengan Za‘farān dan sejenisnya. (7115).
6. Mereka sepakat bahwa apabila air berubah karena terkena najis maka hukumnya najis, baik airnya sedikit maupun banyak. (7216).
7. Mereka berbeda pendapat tentang air yang kurang dari 2 Qullah (7317) yang bercampur dengan najis.
Ukuran 2 Qullah sama dengan 500 Rithl ‘Irāq. Menurut Abū Ḥanīfah, asy-Syāfi‘ī dab Aḥmad – dalam salah satu dari dua riwayatnya – , hukumnya najis. Sedangkan menurut Mālik dan Aḥmad – dalam riwayat lain – . hukumya tidak najis (tetap suci) selama airnya tidak berubah. (7418).
8. Mereka juga sepakat bahwa tidak boleh berwudhu’ dengan air rendaman buah (Nabīdz) secara mutlak. Kecuali Abū Ḥanīfah, karena ada beberapa riwayat yang berbeda darinya.
Diriwayatkan darinya bahwa hukumnya tidak dibolehkan, seperti halnya pendapat jamā‘ah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abū Yūsuf. (7519). Ada pula riwayat darinya bahwa boleh berwudhu’ dengan air perasan kurma yang dimasak dalam perjalanan ketika tidak ada air. Juga ada riwayat darinya bahwa boleh berwudhu’ dengan air tersebut, hanya saja harus ditambah dengan Tayammum. Pendapat ini dipilih oleh Muḥammad bin al-Ḥasan (7620) r.h. (7721).
Catatan: