003 Tauhid-us-Sifat – Permata Yang Indah (Bagian 2)
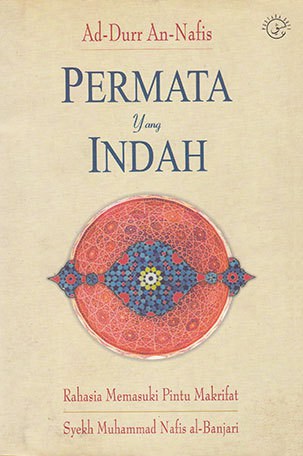
الدر النفيس
للشيخ محمد نفيس ابن إدريس البنجاري
PERMATA YANG INDAH
TITIAN SUFI MENUJU TAUḤĪDULLĀH
Oleh: Syekh Muhammad Nafīs Ibnu Idrīs Al-Banjārī
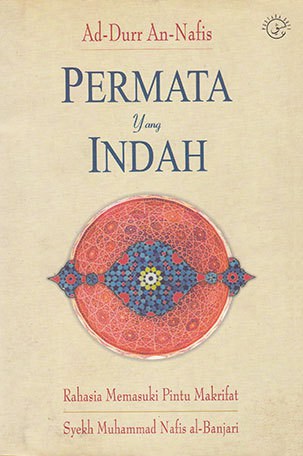
الدر النفيس
للشيخ محمد نفيس ابن إدريس البنجاري
PERMATA YANG INDAH
TITIAN SUFI MENUJU TAUḤĪDULLĀH
Oleh: Syekh Muhammad Nafīs Ibnu Idrīs Al-Banjārī
هو
PASAL TIGA
TAUḤĪD AṢ-ṢIFᾹT
(Bagian 2 dari 2)
كُلًّا نُمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَ هٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا
“Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.” (al-Isrā’ [17]: 20).
Pada maqam seseorang yang telah dianugerahi maqam tersebut, ia akan mendengar segenap panggilan, baik panggilan yang keluar dari lidah yang lahir maupun panggilan yang keluar dari lidah yang batin. Hal ini sama halnya dengan kondisi kata hati yang tidak membedakan antara yang jauh dan yang dekat. Sekalipun panggilan itu berasal dari balik sebuah gunung (dalam naskah tertulis, Jabal Qāf), niscaya ia akan mendengarnya, sebab, keseluruhan alam ini sudah sangat dekat dan akrab dengannya. Berdasarkan sebuah Hadits, sekalian alam ini pada dasarnya menjadi alas (qadam) bagi para wali. Ke mana pun para wali melangkah, alam senantiasa menopong dan melindungi mereka. Hal ini semata-mata adalah karena anugerah dan rahmat Allah s.w.t.
Oleh karena itu, wahai saudaraku! Bersungguh-sungguhlah untuk menuntut hal yang demikian, dalam kaitan dengan Tauḥīd aṣ-Ṣifāt di atas. Ilmu laduni yang telah saya terangkan barusan pada dasarnya menjadi bagian dari keistimewaan seseorang yang telah mencapai Tauḥīd aṣ-Ṣifāt. Memang ada banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai maqam tersebut, tetapi bersungguh-sungguhlah! Senantiasalah berdoa kepada Allah, karena Allah akan memperkenankan doa orang yang meminta! Perkenanan doa ini telah dijanjikan secara langsung oleh-Nya:
اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan bagimu.” (al-Mu’min [40]: 60).
Wahai saudaraku! Dalam upaya menggapai titian yang akan mengantarkan anda kepada Maqam Tauḥid aṣ-Ṣifāt, kiranya menarik untuk dicermati pemahaman pelbagai kalangan dan mazhab dalam membincang hakikat sifat itu sendiri. Persoalan yang kerap menciptakan arus pertentangan di antara ulama dalam hal ini adalah apakah sifat itu dikaitkan (diberi) dengan zat ataukah sesuatu yang lain?
‘Ulamā’ uṣūl ad-Dīn, yakni dari golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā‘ah r.a. berpendapat bahwa semua sifat adalah qadīm (kekal), sebagaimana halnya dengan zat. Ke-qadīm-an Sifat adalah sama dengan ke-qadīm-an zat. Demikian juga wujudnya, adalah sama dengan zat. Sehingga, di antara sifat dan zat, keduanya tidak meninggalkan satu pun perbedaan. Namun demikian, sifat merupakan makna yang berdiri pada zat; zatlah yang memberi makna pada sifat, sehingga pertambahan yang terjadi pada sifat merupakan pengaruh langsung yang dimunculkan oleh zat. Pengaruh zat terhadap sifat ini dapat dilihat dari ungkapa-ungkapan teologis semisal: Allāh Qādir bi Qudratih (Allah Berkuasa atas Kekuasaan-Nya), Allāh Murīd bi Irādatih (Allah Berkehendak atas Kehendak-Nya), Allāh ‘Alim bi ‘Ilmih (Allah Mengetahui dengan Ilmu-Nya), Allāh Ḥayy bi Ḥayātih (Allah Hidup dengan Kehidupan-Nya), Allāh Samī‘ bi Sam‘ih (Allah Mendengar dengan Pendengaran-Nya), Allāh Baṣīr bi Baṣrih (Allah Melihat dengan Penglihatan-Nya), dan Allāh Mutakallim bi Kalāmih (Allah Berkata-kata dengan Kalam-Nya).
Sementara para Sufi (ahl at-taṣawwuf), yakni orang-orang yang mengenal Allah (‘ārifīn bi Allāh) q.s., berpandangan bahwa sifat tidak lain dan tidak bukan adalah diri yang disifati (mauṣūf) itu sendiri, yakni diri zat. Akibatnya, sebagaimana halnya dengan zat, yang disifati, sifat tidak mengalami penambahan. Itulah sebabnya, menurut para Sufi, dikenal – sehingga kita semua harus mengakui – ungkapan-ungkapan seperti: Allāh Qādir bi Żātih (Allah Berkuasa atas Zat-Nya), Allāh Murīd bi Żātih (Allah Berkehendak atas Zat-Nya), Allāh ‘Ᾱlim bi Żātih (Allah Mengetahui atas Zat-Nya), Allāh Samī‘ bi Żātih (Allah Mendengar atas Zat-Nya), Allāh Baṣīr bi Żātih (Allah Melihat atas Zat-Nya), dan Allāh Mutakallim bi Żātih (Allah Berkata-kata atas Zat-Nya).
Syaikhunā al-‘Ᾱrif bi Allāh Maulānā asy-Syaikh Ṣiddīq Ibn ‘Umar Khān, murid dari al-Marḥūm al-Quṭb ar-Rabbānī Maulānā asy-Syaikh Muḥammad Ibn ‘Abd al-Karīm as-Sammān al-Madanī r.a. memiliki pandangan yang sama dengan pandangan Sufi tersebut, bahkan ia menegaskan bahwa:
“Selain pandangan Sufi tidak mungkin dapat diterima. Penerimaan terhadap konsepsi itu dapat dipahami melalui jalan kasyf (penyingkapan) dan musyāhadah (penyaksian). Oleh karena itu, konsepsi yang menyatakan bahwa sifat adalah Diri Mauṣūf merupakan konsepsi yang didukung oleh basis argumentasi yang kokoh (ṡābit) di kalangan para Sufi. Orang yang menempuh jalan kasyf dan musyāhadah niscaya dibukakan oleh Allah s.w.t. dinding yang selama ini menutupinya untuk menyaksikan Sifat-Nya. Sehingga, orang-orang semacam ini tidak akan melihat dan mendapatkan lagi sifat yang berdiri melekat (inheren) pada makna yang dimunculkan oleh zat – sebagaimana pandangan yang dianut oleh kalangan ahl uṣūl ad-Dīn. Orang-orang ini hanya akan menjumpai bahwa sifat itu berdiri di atas zat jua. Namun tentu bukan zat yang memberikan makna pada sifat, karena keduanya tidaklah berbeda.”
Untuk mengonter pandangan ahl uṣūl ad-Dīn di atas, kaum Sufi mempergunakan argumen rasional (dalil aqli), dengan mengatakan bahwa: “Jika ternyata sifat memperoleh maknanya dari zat, maka pastilah Allah itu Majhūl (Tidak Dikenal), karena Dia masih menghendaki sifat-sifat yang akan memperkenalkan-Nya.” Mahasuci Allah dari yang demikian! Allah Mahamakrifat dari segala yang makrifah.
Adapun pandangan bahwa sifat berbeda dari zat, dan bahkan bisa mengalami penambahan – sebagaimana juga dianut oleh ahl uṣūl ad-Dīn – semata-mata didasarkan atas argumentasi aqliah dan keyakingan (i‘tiqād). Argumentasi aqliah yang ditempuh dalam hal ini adalah prosedur logis, karena pandangan tersebut didasarkan pada ism musytāq. Ism musytāq adalah ism (kata benda) yang dibentuk dari ism lainnya, misalnya “qādir”, yang merupakan ism bentukan dari “qudrah”. Jika ism musytāq merupakan ism bentukan maka secara pasti ia memerlukan musytāq minh (orisinalitas bentuknya). Musytāq minh dalam hal ini adalah mutlak dari ism maṣdar, yang merupakan asal-usul kata benda dalam bahasa Arab. Jadi, jika qādir sebagai ism musytāq merupakan ism fā‘il (pelaku), maka musytāq minh-nya yang tidak lain dari ism maṣdar-nya dalah qudrah. Qudrah sebagai maṣdar menjadi sifat dalam hal ini, yang tentu, menurut mereka, harus dibedakan dari zat. Namun demikian, lanjut mereka, sifat tidak mempunyai wujud tertentu yang berdiri sendiri, melainkan hanya wujud zat. Jadi, kendati sifat berbeda dari zat, namun segala sesuatunya sifat sangat bergantung pada zat, termasuk misalnya dalam masalah ke-qadīm-an-nya.
Pandangan ini secara jelas menunjukkan kekurang-sempurnaan karena ia masih membedakan antara sifat dan zat. Padahal, jika mereka – yang menganut pandangan tersebut – mau melakukan musyāhadah, niscaya mereka akan menemukan bahwa di antara keduanya pasti akan melebur menjadi satu; di antara keduanya pada hakikatnya sama. Pandangan inilah yang dianut oleh para Sufi, yang telah benar-benar menyaksikan kebenaran pendapat mereka. Dengan demikian, jika para “pembeda” tersebut juga mau “menyaksikan”, niscaya mereka akan menemukan bahwa apa yang selama ini mereka yakini ternyata keliru, dan apa yang selama ini memiliki kebenaran adalah pendapat para Sufi.
Kekeliruan dan kebenaran ini dapat diumpamakan dengan ceritera seseorang mengenai sifat Ḥajar Aswad (Batu Hitam Suci di Ka‘bah) di Makkah kepada seseorang yang berada di Jawa, yang belum pernah melihat secara langsung Ḥajar Aswad tersebut. Dikatakan kepada orang Jawa ini bahwa Ḥajar Aswad berwarna sangat hitam. Tanpa berpikir terlalu jauh, ia pun meyakininya, dengan membayangkan bahwa ada titik hitam yang melekat pada Batu Suci itu. Orang Jawa ini sebenarnya telah membayangkan Ḥajar Aswad dalam konteks fisiknya. Ia menempuh jalur ini, sebab akalnya semata tidak mampu membayangkannya tanpa melibatkan pembayangan fisik hitamnya tersebut. Maka, suatu ketika ia pergi ke Makkah, dan mendatangi Ḥajar Aswad dimaksud guna melihat langsung dan membuktikan kebenaran apa yang dibayangkannya selama ini tentang sifat Ḥajar Aswad tersebut. Ternyata, ia menemukan bahwa Ḥajar Aswad memang berwarna hitam, tetapi, ia bukanlah sebuah batu yang kemudian ada titik-titik hitam yang melekat padanya. Ḥajar Aswad adalah sebongkah batu yang kesemuanya berwarna hitam. Dengan demikian, pupuslah keyakinannya selama ini, sebab kehitaman Ḥajar Aswad yang merupakan sifatnya tersebut ternyata juga merupakan zatnya sendiri. Dengan kata lain, kehitaman Ḥajar Aswad di samping menjadi sifatnya juga menjadi zatnya.
Jadi, sekali lagi bahwa betapa benar pendapat yang digagas oleh para Sufi tersebut! Namun, beberapa kalangan, khususnya Mu‘tazilah, tampaknya mengajukan kritik keras terhadap pendapat Sufi tersebut, sehingga di sini juga patut dicermati bagaimana respon ketidak-setujuan mereka. Secara garis besar, kalangan Mu‘tazilah menganggap bahwa klaim Sufi yang menyatakan bahwa sifat adalah zat dan bahwa sifat tidak mengalami penambahan merupakan klaim yang menganut konsep ittiḥād, yaitu konsep penyatuan. Konsep ittiḥād diumpamakan kaum Mu‘tazilah dengan adanya wujud yang berdiri sendiri (istiqlāl) dalam zat di satu sisi dan wujud yang berdiri sendiri dalam sifat di sisi lain. Kedua wujud dicampur laksana dituangkannya gula ke dalam air yang mendidih. Mahasuci Allah dari persangkaan kaum Mu‘tazilah yang bid‘ah lagi fasik itu! Pandangan kaum Sufi sama sekali tidaklah seperti itu, sebab para Sufi tidak membuat polarisasi (pemisahan) dua wujud yang berbeda yang kemudian disatukan sehingga tidak bisa lagi dibedakan; sebagaimana contoh dari Mu‘tazilah tentang gula dan air yang kemudian menjadi, misalnya, secangkir teh. Kaum Sufi, sebagaimana dikemukakan di atas, tidaklah menganut konsep penyatuan dari dua entitas yang berbeda, melainkan menganggap bahwa keduanya tidaklah berbeda.
Akhirnya, di akhir kesempatan sub ini, saya ingin mengatakan bahwa memang ada banyak persoalan yang muncul manakala kita mendiskusikan sifat ini, tetapi di sini juga saya ingin menegaskan bahwa Maqam Tauḥīd aṣ-Ṣifāt, yang telah dipaparkan secara panjang-lebar di atas, pada dasarnya merupakan maqam yang memiliki posisi kuat lagi kokoh (rāsikh). Ketika penyingkapan (tajallī) sifat-sifat Allah telah dipupuskan di dalam hati seorang hamba, maka Allah s.w.t. akan menganugerahkan suatu kekuatan yang dapat menjaminnya untuk menghadapi penyingkapan (tajallī) zat, in sya’ Allah. Maqam Tauḥīd aṣ-Ṣifāt itulah yang menyampaikan seorang ‘ārif (gnostik) menuju maqam yang berada di atasnya, yaitu Maqam Tauḥīd aż-Żāt. Inilah maqam yang keempat dari segala macam maqam kaum ‘ārifīn.