001 Tauhid-ul-Af’aal – Permata Yang Indah (Bagian 3)
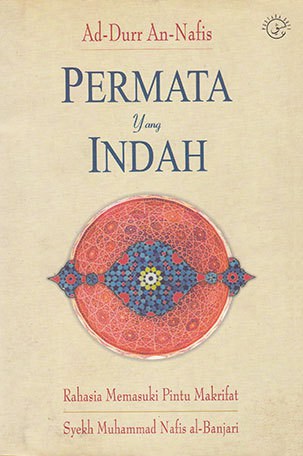
الدر النفيس
للشيخ محمد نفيس ابن إدريس البنجاري
PERMATA YANG INDAH
TITIAN SUFI MENUJU TAUḤĪDULLĀH
Oleh: Syekh Muhammad Nafīs Ibnu Idrīs Al-Banjārī
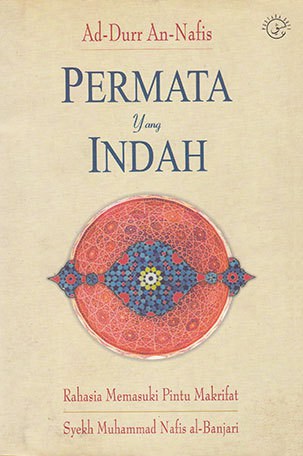
الدر النفيس
للشيخ محمد نفيس ابن إدريس البنجاري
PERMATA YANG INDAH
TITIAN SUFI MENUJU TAUḤĪDULLĀH
Oleh: Syekh Muhammad Nafīs Ibnu Idrīs Al-Banjārī
هو
PASAL SATU
TAUḤĪD AL-AF‘ĀL
Ketiga madzhab yang telah disebutkan di atas ini, termasuk madzhab yang dianut Asy‘ariyyah, keyakinannya muncul di atas konsepsi yang tertutup (gisyāwah), sehingga mereka semua tidak bisa melihat yang batin, sebagaimana yang mampu disaksikan oleh madzhab yang keempat.
Syaikh ‘Abd-ul-Wahhāb asy-Sya‘rānī menyebutkan bahwa Syaikh Muḥy-id-Dīn Ibn ‘Arabī r.a. menjelaskan di dalam bab 422 dari al-Futūḥāt-ul-Makkaiyyah-nya bahwa:
“Segala amal perbuatan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah berasal dari Allah s.w.t. Hanya saja, perbuatan-perbuatan itu kemudian disandarkan kepada kita sebagai hamba-Nya, yang berarti bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah untuk kita sendiri.”
Kita dipersiapkan oleh Tuhan sebagai sosok-sosok yang akan menerima siksa ataupun pahala. Melalui perbuatan-perbuatan itu, Tuhan pada dasarnya ingin menguji hamba-hambaNya. Tuhan ingin melihat siapakah di antara hamba-hambaNya itu yang akan masuk ke dalam hasrat Iḥsān. Jika seseorang telah masuk ke dalam lingkungan ini, maka ia akan mampu menampik semua penutup yang akan menghalangi perjalanannya. Ia pada akhirnya akan ber-musyāhadah dengan Allah s.w.t. Jika seseorang telah ber-musyāhadah, maka ia akan selalu takut untuk menisbatkan perbuatan-perbuatannya dan juga perbuatan-perbuatan makhluk lainnya dengan diri mereka sendiri; ia sepenuhnya akan mengakui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut muncul dari Allah s.w.t.
Namun demikian, harus disadari bahwa kendati semua perbuatan berasal dari Allah, Allah Sendiri sebenarnya telah memberikan fasilitas-fasilitas dalam diri manusia untuk menjalani kehidupan mereka sendiri di dunia ini. Allah s.w.t. telah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga dengan ilmu pengetahuan tersebut kita mampu menyeleksi perbuatan yang kira-kira layak dikerjakan ataupun sebaliknya. Sehingga, karena Allah tidak pernah memerintahkan untuk melaksanakan perbuatan tidak baik, maka segala perbuatan tercela yang tercipta dari tangan-tangan kita adalah sepenuhnya menjadi tanggung-jawab kita sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan firman-Nya:
مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ
“Apa saja nikmat (kebaikan) yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana (keburukan, kejahatan) yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.” (an-Nisā’ [4]: 79).
Maksudnya adalah bahwa tidak seorang pun di antara kita yang melakukan kebaikan melainkan kebaikan itu berasal dari Allah, dan tidak seorang pun di antara kita yang melakukan kejahatan melainkan kejahatan itu berasal dari diri kita sendiri.
Syaikhunā al-‘Allāmah Maulānā asy-Syaikh Yūsuf Abū Dzarrah al-Mishrī ketika sedang memberikan pelajaran kepada para jamaah di al-Masjid-ul-Ḥarām, mengatakan bahwa:
“Allah s.w.t. tidak mungkin melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu terlahir dari tangan-tangan manusia jua yang sebenarnya sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk meninggalkannya.”
Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. tentang doa iftitāḥ (wasy-syarru laisa ilaik – kejahatan bukan atas-Mu), Syaikh Ibn Ḥajar di dalam Syarḥ-ul-Arba‘īn berpendapat bahwa: “Kejahatan itu bukanlah bersumber dari Allah s.w.t. Etika (Ādāb) bahkan mengajarkan kita untuk tidak menyandarkan hal-hal buruk yang dapat menghina Allah s.w.t. Kita tidak harus mengatakan, misalnya: “Ya Allah Yang Menciptakan anjing dan babi,” sekalipun Dia sebetulnya memang menciptakannya. Dengan etika yang niscaya dijunjung tinggi, kita harus menisbatkan hanya hal-hal yang baik kepada-Nya.”
Syaikh ‘Abd-ul-Wahhāb asy-Sya‘rānī q.s. – salah seorang ulama besar Asy‘ariyyah – pernah bertanya kepada gurunya, Sayyidī ‘Alā al-Khawwāsh mengenai hakikat usaha. Sang guru menjawab bahwa:
“Hakikat usaha adalah menggantungkan kehendak atau keinginan yang mungkin dengan melakukan perbuatan-perbuatan, dan kemudian diperoleh takdirnya dari Ilahi. Itulah yang disebut dengan usaha, yang bersifat kemungkinan, sebab kehendak kita, yang kemudian kita kejawantahkan ke dalam perbuatan-perbuatan, sangat bergantung kepada kehendak Ilahi.”
Syaikh asy-Sya‘rānī q.s. juga selanjutnya mengatakan bahwa ia pernah mendengar gurunya tersebut berpendapat bahwa: “Wajib atas hamba untuk memahami bahwa makhluk tidak mampu memberi bekas dalam memperbuat segala sesuatu. Artinya, makhluk tidak mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Namun demikian, kepada mereka itu dibebankan terjadinya hukum-hukum alam, yang berpengaruh kepada penegakan hukum syarī‘ah bagi manusia.” Oleh karena itu, hendaklah anda pahami, karena kebanyakan manusia tidak memahami hal ini!”
Sang guru, yang juga disebut sebagai Sayyid al-Khawwāsh itu, juga menerangkan bahwa:
“Apabila al-Ḥaqq hendak memberi makna bagi perbuatan manusia, maka wujud dari perbuatan itu tidaklah diperlihatkan-Nya secara jelas melainkan hanya menunjukkan materi (māddah) dari perbuatan itu. Sebab, sangat tidak mungkin perbuatan itu dapat berdiri sendiri sementara ia tidak ditempatkan atau diberikan pada hamba.”
Syaikh ‘Abd-ul-Wahhāb asy-Sya‘rānī q.s. juga mengakui bahwa ia pernah mendengar saudaranya, Afdhāl-ud-Dīn, berkata:
“Bagi manusia yang diberi oleh-Nya sifat kemungkinan dari perbuatannya pada dasarnya tidak memiliki qudrah (kekuasaan). Manusia hanya dapat menerima ketentuan-ketentuan Ilahi atas segala usaha yang dilakukannya, sebab qudrah itu hanya dimiliki oleh-Nya. Qudrah tidak lain adalah Sifat Ilahi. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan Ilahi atas qudrah-Nya ini tidak harus dan tidak perlu disertai dengan alasan-alasan.”
Syaikh Afdhāl-ud-Dīn mengatakan bahwa ia sependapat (muwāfiqah) dengan kalangan Asy‘ariyyah yang menegaskan bahwa qudrah yang ada pada hamba merupakan akibat dari Qudrah Allah, dan sama sekali tidak ada qudrah yang berdiri sendiri kepada hamba.
Sebagaimana dipaparkan Syaikh ‘Abd-ul-Wahhāb asy-Sya‘rānī q.s., Syaikh Muḥy-id-Dīn Ibn ‘Arabī r.a. dalam Bab 120 dari al-Futūḥāt-ul-Makkaiyyah-nya, mengatakan bahwa:
“Merupakan masalah yang amat sukar jika kita coba menafikan Sang Pelaku ini, sebab ini berkaitan langsung dengan perbuatan-Nya.”
Syaikh Ibn ‘Arabī sendiri mengakui bahwa ia sangat kesulitan dalam memecahkan pelbagai persoalan di seputar masalah ini. Allah, katanya, tidak membukakan lebar-lebar pintu hati pengetahuannya tentang masalah ini. Pengetahuannya tentang masalah ini tidak begitu jelas, melainkan samar-samar. Padahal, ini barulah masalah yang berkenaan dengan Perbuatan-Nya, dan belum merambah pada wilayah kajian yang berkaitan dengan Sang Pelaku (Fā‘il) Sendiri. Pada (tahun) 633 Hijriah ketika Ibn ‘Arabī mencoba menulis dan merangkai kata-kata di seputar masalah tersebut, ia merasakan betapa sulit untuk menafsirkan makna “usaha”. Kesulitan ini muncul setelah ia mencoba membandingkan pemahaman yang ditawarkan oleh kalangan Ahli Sunnah dengan pendapat kalangan Mu‘tazilah. Selanjutnya, berikut pengisahan konsepsinya:
“Harapanku adalah bahwa Allah s.w.t. akan membukakan pintu taufik-Nya kepadaku dengan menyingkap pandanganku. Bagiku, tidak ada satu pun makhluk yang mendahului Allah. Berdasarkan firman-Nya, dari Sirr Allah-lah awal kejadian seluruh makhluk. Perbuatan makhluk tidak lain adalah warisan Ilahi. Pemahaman inilah yang aku yakini. Maka, jika engkau melihat sesuatu hal yang baru, hal itu bukanlah hasil dari ciptaan manusia. Tuhan menegaskan bahwa: “Akulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu.” Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tanpa oleh sebab-sebab. Tuhan menciptakan ‘Īsā, misalnya, tanpa didahului oleh sebab-sebab yang lazim dari sebuah proses kelahiran seorang manusia. Bayangkan, apakah manusia mampu melakukan hal yang sama? Tentu saja tidak! Tetapi anehnya, sekalipun manusia menyadari hal ini, mereka masih pada mempertanyakan tanpa memberikan sikap keimanan tegas seketika. Firman Allah:
لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُوْنَ
“Dan tidak ditanya apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai.” (al-Anbiyā’ [21]: 23).
Dalam konteks ini, Syaikh ‘Abd-ul-Wahhāb asy-Sya‘rānī q.s. menegaskan: “Fa ta’ammalhu fa’innahu nafīs.” (Renungkanlah, karena sesungguhnya Dia itu Indah).