001 Taqlid Dalam Permasalahan Ushuluddin – Jam’-ul-Jawaami’
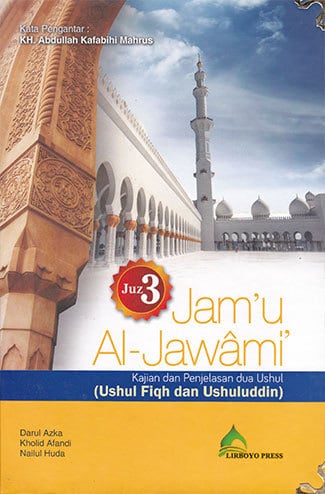
JAM‘-UL-JAWĀMI‘
Kajian dan Penjelasan dua Ushul
(Ushul Fiqh dan Ushuluddin)
Penyusun:
Darul Azka
Kholid Afandi
Nailul Huda
Penerbit: Santri salaf crew.
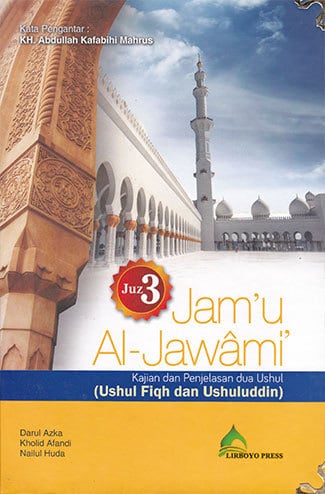
JAM‘-UL-JAWĀMI‘
Kajian dan Penjelasan dua Ushul
(Ushul Fiqh dan Ushuluddin)
Penyusun:
Darul Azka
Kholid Afandi
Nailul Huda
Penerbit: Santri salaf crew.
Kajian dan Penjelasan dua Ushul
(Ushul Fiqh dan Ushuluddin)
مَسْأَلَةٌ: اُخْتُلِفَ فِي التَّقْلِيْدِ فِيْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ، وَ قِيْلَ النَّظَرُ فِيْهِ حَرَامٌ.
وَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ لَا يَصِحُّ إِيْمَانُ الْمُقَلِّدِ، وَ قَالَ الْقُشَيْرِيُّ مَكْذُوْبٌ عَلَيْهِ. وَ التَّحْقِيْقُ إِنْ كَانَ أَخْذَ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ مَعَ احْتِمَالِ شَكٍّ أَوْ وَهْمٍ فَلَا يَكْفِيْ، وَ إِنْ كَانَ جَزْمًا فَيَكْفِيْ خِلَافًا لِأَبِيْ هَاشِمٍ.
Permasalahan: Diperdebatkan hukum taqlīd dalam ushūluddīn (permasalahan pokok-pokok agama). Dikatakan (dalam sebuah pendapat), bahwa nadhar (olah pikir) dalam permasalahan ushūluddīn adalah haram.
Dan diriwayatkan dari Imām al-Asy‘ariy bahwa keimanan seseorang melalui taqlīd tidaklah sah, Berkata al-Qusyairiy, riwayat pendapat dari al-Asy‘ariy ini dipalsukan atas nama beliau. Dan, pendapat yang taḥqīq adalah, jika yang dimaksud taqlīd adalah mengambil pendapat orang lain dengan tanpa ḥujjah (dasar), dengan masih adanya kemungkinan keraguan (syakk) atau prasangka (wahm), maka belum mencukupi. Dan jika dengan kemantapan keyakinan, maka mencukupi. Ini berbeda dengan pendapat Abū Hāsyim.
TAQLĪD DALAM PERMASALAHAN USHŪLUDDĪN
Ushūluddīn atau pokok-pokok agama adalah permasalahan-permasalahan terkait dengan akidah dan keyakinan pokok dalam agama, seperti barunya alam, wujudnya Pencipta, sifat-sifat wajib Tuhan, sifat-sifat mustahil-Nya, terutusnya para rasul, keadaan hari berbangkit, dan permasalahan-permasalahan lainnya, sebagaimana akan dipaparkan kemudian. Ilmu tentang ushūluddīn oleh sebagian orang disebut dengan ilmu kalam, karena awal mula permasalahan yang mengemuka adalah perdebatan seputar sifat kalam bagi Allah.
Jam‘-ul-Jawami‘ membagi permasalahan dalam ilmu kalam ini dalam dua bagian: ‘ilmiy, yakni permasalahan yang wajib diyakini; dan ‘amaliy bukan ‘ilmiy, yakni permasalahan yang tidak wajib diketahui dalam pokok akidah, ia hanyalah simulasi dari oleh pikir. Keduanya dipilah, dan bagian kedua dikategorikan dalam bagian ilmu hikmah dan thabī‘ah (fisika). Akan tetapi pendapat yang taḥqīq, adalah bahwa bagian kedua bukanlah termasuk dalam bagian ilmu ushūluddīn, akan tetapi masuk dalam bagian ilmu kalam. Sedangkan bagian pertama, jika bersamaan dengannya ada unsur menegakkan argumentasi rasio dalam menuturkan pendapat-pendapat ahli bid‘ah dan falāsifah (filosof atheis), maka itu termasuk ilmu kalam; dan jika tidak, maka termasuk dalam bagian ilmu ushūluddīn. (341).
Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pembahasan taqlīd, bolehkah taqlīd dilakukan dalam permasalahan ushūluddīn? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama’.
Pendapat pertama, sebagaimana dipedomani mayoritas ulama’, di antaranya Abū Isḥāq al-Isfirāyīniy, dan diunggulkan oleh Imām ar-Rāzī dan al-Amudiy, bahwa taqlīd dalam permasalahan ushūluddīn adalah haram. Karena ikut-ikutan dalam masalah akidah keyakinan itu dicela dalam al-Qur’ān. Allah berfirman:
بَلْ قَالُوْا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُوْنَ (الزخرف: 22)
“Bahkan mereka berkata: “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.” (QS. Az-Zukhruf: 22).
Di satu sisi, dalam permasalahan akidah, Allah mencela sikap yang mendasarkan pada dugaan atau ketiadaan keyakinan. Sebagaimana firman-Nya:
وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ. (الأنعام: 116)
“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. al-An‘ām: 116).
Sehingga, dalam permasalahan ushūluddīn ini, melakukan nadhar (olah pikir) wajib hukumnya. Karena yang dicari dalam masalah ini adalah keyakinan. Allah berfirman:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ (مُحَمَّدٌ: 19).
“Maka yakinilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah.” (QS. Muḥammad: 19)
Allah memerintahkan Rasūl-Nya untuk meyakini, atau mengupayakan terwujudnya sebuah keyakinan bahwa Tidak ada tuhan selain Allah. Dan Rasūlullāh telah melakukan upaya pencapaian keyakinan itu. Sedang kita umatnya diperintahkan untuk mengikuti beliau. Allah berfirman:
وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (الأعراف: 158)
“Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-A‘rāf: 158)
Al-Qur’ān Sūrah Muḥammad: 19 di atas memerintahkan pencapaian keyakinan dalam permasalahan waḥdāniyyah (keesaan Allah). Dan permasalahan tentang akidah lainnya diqiyaskan.
Pendapat kedua, taqlīd dalam permasalahan ushūluddīn diperbolehkan. Pendapat ini dipedomani oleh ‘Ubaidullāh bin al-Ḥasan al-‘Anbāriy dan yang lain. Karena Rasūlullāh s.a.w. menganggap cukup iman dari orang-orang ‘Arab Badui (suku pedalaman) dengan hanya berucap dua kalimat syahadat yang didasarkan pada keyakinan yang mantap, dan mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam bernalar dan berolah pikir (nadhar). Dan, permasalahan selain iman diqiyaskan.
Pendapat ketiga, bahwa taqlīd dalam permasalahan ushūluddīn adalah wajib; sehingga bernalar (nadhar) dalam masalah ushūluddīn ini hukumnya haram, karena nadhar dianggap berpengaruh dalam menjerumuskan seseorang ke dalam syubhat (keraguan akidah) dan jalan kesesatan, sebab berbeda-bedanya kekuatan nalar dan olah pikir.
Argumentasi dari dua pendapat di atas disanggah, bahwa tidak benar jika orang-orang ‘Arab Badui bukanlah ahli nadhar, karena sebenarnya yang dipersyaratkan hanyalah nadhar versi orang awam. Sebagaimana dialog al-‘Ushmu‘iy dengan sebagian orang Badui, “Dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu?” Si Badui menjawab: “Kotoran unta menunjukkan adanya unta, dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang lewat, maka langit yang penuh bintang, dan bumi yang terhampar, tidakkah menunjukkan atas adanya Tuhan Sang Maha Pengasih dan Maha Mengetahui?” Adapun nadhar versi ulama’ mutakallimin yang berupa perumusan dalil dan penjabarannya, langkah antisipasi keraguan dan syubhat dalam masalah akidah, maka hukumnya adalah fardhu kifāyah bagi orang yang berkemampuan untuk melakukannya, dan cukuplah hanya sebagian dari mereka yang menekuninya. Selain dari mereka, yakni orang-orang awam yang dengan melakukan pembahasan ilmu kalam secara mendalam akan menjerumuskan mereka ke jurang keraguan dan kesesatan, maka haram bagi mereka melakukan aktivitas nadhar seperti yang dilakukan para ulama’ mutakallimin. Cukuplah bagi mereka nadhar versi kalangan awam, sebagaimana paparan di muka.
Berdasar ketiga pendapat di atas, keimanan seseorang melalui taqlīd dianggap tidak sah. Menurutnya, keabsahan iman hanya bisa dicapai melalui proses nadhar. Bahkan, ada riwayat dari Imām al-Asy‘ariy yang mendukung pernyataan ini, bahwa keimanan muqallid dinyatakan tidak sah. Sebagian kalangan mengkritik tajam pendapat ini, bahwa pendapat semacam itu berkonsekuensi takfīr (vonis kufur) pada orang-orang awam yang notabene mayoritas mu’minin. Menanggapi tundingan ini, beberapa tawaran klarifikasi diajukan (352).
Catatan: