Sekilas Pandang
Dengan taḥqīq dalam masalah ini dan faktor pendorong perselisihan di dalamnya, nampak jelas bahwa perselisihan dan perdebatan di dalamnya lebih banyak dari yang dikandungnya, yakni kepada yang formal lebih dekat daripada kepada yang hakiki, dan tidak ada wujudnya dalam perbuatan.
Taḥqīq-nya adalah: Selama mereka sepakat bahwa mengadakan perjalanan ke masjid Nabi untuk menyampaikan salam kepada Rasūlullāh s.a.w., dan sepakat bahwa salam kepada Rasūlullāh s.a.w. juga bisa dilakukan tanpa mengadakan perjalanan.
Jadi, tidak akan menjadi mudah bagi manusia untuk mengadakan perjalanan untuk menyampaikan salam tanpa melalui masjid, dan hal itu tidak terlintas dalam pikiran manusia. Demikian juga mengadakan perjalanan untuk shalat di masjid Nabi tanpa memberikan salam kepada Rasūlullāh s.a.w., tidak akan tebersit dalam pikiran manusia, maka baginya yang demikian dan tidak ada permisahan antara satu dengan lainnya, karena masjid Nabi tiada lain selain rumah beliau, dan bukankah rumahnya adalah bagian dari masjid, sebagaimana dalam hadits raudhah: (مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.) “Apa yang ada di antara rumah dan mimbarku adalah salah satu dari taman surga.”
Ini adalah kuatnya ikatan antara rumah dengan mimbar beliau di masjidnya.
Dari segi lain, apakah seseorang memberikan salam kepadanya dari dekat, untuk mendapatkan keutamaan balasan salam dari Nabi s.a.w., kecuali salamnya dari dekat dan dari masjid itu sendiri.
Juga apakah ziarah itu menjadi perbuatan yang agung kecuali masuk masjid dan shalat terlebih dahulu dengan tahiyat-ul-masjid?
Dengan demikian, tidak ada pemisahan bagi bepergian ke masjid dengan berziarah kepada Rasūlullāh s.a.w., dan bukan karena kunjungan kepada beliau dari masjid, maka tidak ada motif untuk pertentangan ini.
Di sini terhadap selayang pandang lain, bahwa sabda Nabi s.a.w.: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ رُوْحِيْ حَتَّى فَأَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ) “Tidak seorang pun memberikan salam kepadaku kecuali pasti Allah akan mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku membalas salam kepadanya,” maka penyebutan semua qayyid dari dekat atau jauh termasuk yang menunjukkan kepada keumuman dari segi kedatangannya untuk memberikan salam kepada beliau.
Oleh karena itu, dikatakan: “Ini adalah keutamaan yang agung dan tidak mudah bagi yang jauh mendapatkannya kecuali dengan mengadakan perjalanan sebagai sarana untuk mendapatkannya dan sarana penempati kedudukan tujuan seperti wajib, sunnah, atau mubah, seperti berlari pada hari Jum‘at hukumnya adalah wajib, karena menunaikan shalat Jum‘at, misalnya, disunnahkan, karena memperindah untuk menjalankannya sunnah dan perumpamaan lainnya adalah mempersiapkan wewangian untuk menghadirinya.”
Aku melihat Syaikh Ibnu Taimiyyah memperdebatkan masalah ini, akan tetapi ia membuat contoh-contoh yang bisa diperdebatkan, maka ia berkata: “Tidak semua tujuan itu disyariatkan, sehingga sarananya juga disyariatkan, seperti hajinya perempuan dan keluarnya perempuan ke masjid, karena yang pertama disyaratkan adanya muhrim dan yang kedua disyaratkan adanya idzin suami.”
Perdebatan bisa ditujukan kepadanya karena bepergiannya perempuan secara mutlak dilarang kecuali bersama muhrim, baik ke masjid haji, maupun lainnya.
Keluarnya perempuan ke masjid tidaklah dituntut pada hukum asalnya, akan tetapi, jika ia meminta idzin maka ia diidzinkan keluar, sehingga hukum asalnya adalah larangan hingga mendapatkan idzin.
Terhadap hal tersebut dikatakan: “Jika bepergian itu tidak disyariatkan baginya, maka bagi pelakunya tidak ada bagian keutamaan dan tidak mendapatkan balasan salam dari beliau.”
Jika demikian adanya, maka peringatan harus diberikan kepadanya ketika menjelaskan keutamaannya, karena tidak adanya penundaan penjelasan, sehingga seakan-akan dikatakan: “Maka Dia membalas salam kepadanya,” kecuali orang yang bepergian untuk itu. Atau dikatakan: “Barang siapa mendatangiku dari dekat, kemudian ia mengucapkan salam kepadaku…..” Akan tetapi, hadits tidak datang seperti ini dan hadits tetap dalam keumumannya.
Hendaknya diketahui bahwa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah membedakan antara salam kepada Rasūlullāh s.a.w. dengan salam kepada orang Islam pada umumnya, karena Rasūlullāh s.a.w. memiliki hak dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang lain berupa kewajiban cinta, pengagungan, dan keharusan shalawat serta salam dalam shalat kita dan ketika masuk dan keluar dari masjid. Bahkan ketika mendengar nama beliau disebutkan, yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Sebagaimana ziarah kepada selain beliau untuk berdoa dan meminta rahmat kepadanya, sementara ziarah kepada Nabi s.a.w. adalah agar Allah s.w.t. membalaskan salam kepada rohnya sehingga beliau bisa membalas salam kepada kita.
Ziarah kepada selain beliau di semua tempat di dunia tidak memiliki keistimewaan apa pun, sementara ziarah kepada beliau dari masjidnya, dan beliau telah diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada orang lain.
Saya yakin masalah ini jika bukan karena perselisihan antara orang yang semasa dengan Syaikh Islam dan Syaikh sendiri pada yang selainnya, tidak akan ada tempat dan ruang.
Akan tetapi, mereka mendapati permasalahan ini sebagai permasalahan yang sensitif, penuh sentuhan rasa, dan cinta kepada Rasūlullāh s.a.w., maka mereka menanggapi pernyataannya ketika ia berkata: “Penekanan bepergian ini tidak semata-mata untuk ziarah, melainkan karena masjid itu sendiri untuk diziarahi, karena mengamalkan nash hadits yang ada, namun sebagian orang mengada-adakan permasalahan yang tidak dijelaskan secara jelas. Jika pernyataan itu dibawa sebagai penafian sebagai ganti dari pelarangan maka itu akan sesuai, yakni karena ia – raḥimahullāh – tidak melarang berziarah kepada Rasūlullāh s.a.w. atau mengucapkan salam kepada beliau, melainkan sebaliknya menjadi keutamaan dan bentuk taqarrub. Hanya saja nash hadits mengenai penekanan perjalanan ke masjid itu untuk semua hal yang bisa dilakukan di sana, dan di antaranya menyampaikan salam kepada Rasūlullāh s.a.w., sebagaimana ia tegaskan sendiri dalam kitabnya.
Di sebagian risalah dan penolakannya, Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah berkata:
Pasal
Aku telah menyebutkan dalam buku yang aku tulis dalam hal manāsik, bahwa bepergian ke masjid dan berziarah ke kuburan beliau adalah amal shalih yang disunnahkan.
Aku telah menyebutkan dalam berbagai manāsik haji tentang kesunnahan hal tersebut dan bagaimana memberi salam kepada beliau, dan apakah menghadap ruangan atau qiblat terdapat dua pendapat?
Mayoritas mengatakan bahwa ia menghadap ruangan seperti Mālik, Syāfi‘ī, dan Aḥmad, hingga ia berkata: Shalat di-qashar dalam bepergian yang disunnahkan ini dengan kesepakatan Imām kaum muslim. Tidak seorang pun dari Imām kaum muslim mengatakan bahwa bepergian ini tidak di-qashar shalatnya dan tidak seorang pun melarang bepergian ke masjid beliau, meski orang yang bepergian ke masjid beliau menziarahi kuburan beliau, bahkan ini termasuk amal shalih yang utama dan tidak satu pun dari perkataanku dan perkataan orang selainku melarang hal itu, serta tidak ada larangan syar‘i tentang menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih. Juga tidak ada yang disyariatkan untuk menziarahi kuburan-kuburan lainnya.
Hingga ia berkata:
Jika menziarahi kuburan orang Islam biasa memang disyariatkan, maka menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shāliḥ menjadi lebih utama. Akan tetapi, Rasūlullāh s.a.w. memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan orang shalih lainnya, yakni kita diperintahkan untuk memberikan shalawat dan salam kepada beliau pada setiap kali shalat, dan itu diperkuat dalam shalat, ketika adzan, dan pada semua doa. Hendaknya kita juga memberikan shalawat dan salam kepada beliau ketika keluar darinya. Jadi, barang siapa memasuki masjid beliau pastilah ia mengucapkan shalawat dan salam kepada beliau dalam shalatnya.
Bepergian ke masjid beliau disyaratkan, tetapi para ulama membedakan antara beliau dengan selain beliau.
Ketika Mālik tidak menyukainya, dikatakan: “Aku menziarahi kuburan Nabi s.a.w.,” karena maksud syar‘i dari menziarahi kuburan adalah memberikan salam kepadanya dan mendoakan mereka. Salam dan doa tersebut tercapai melalui cara yang paling sempurna dalam shalat di masjidnya dan masjid selainnya, serta ketika mendengar adzan dan dalam setiap doa. Oleh karena itu, disyariatkan memberikan shalawat ketika berdoa, karena beliau lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri.” Pembahasan selesai.
Jika ini merupakan pendapatnya, maka masalahnya adalah formal dan tidak hakiki, karena ia menegaskan bahwa bepergian ke masjid beliau disyariatkan, juga menziarahi kuburannya dan memberikan salam kepadanya, termasuk taqarrub yang paling utama dan termasuk amal shāliḥ.
Maksudnya, meski ziarah diniatkan ketika bepergian.
Jika bepergian ke masjid tidak bisa dipisahkan dari salam kepada beliau, maka salam kepada beliau tidak bisa dipisahkan dari shalat di masjid, sehingga tidak ada motif untuk berselisih. Masalah ini menjadi faktor pendorong persilisihan dan perbantahan.
Telah dijelaskan pula keterangan yang dekat dengan makna ini di tempat lain, al-Majmū‘ jld. 27, h. 34: Barang siapa bepergian ke Masjid-ul-Ḥarām, Masjid-ul-Aqshā, atau Masjid Nabawi, maka hendaknya shalat di masjidnya dan Masjid Qubā’, serta berziarah kubur, sebagaimana ditetapkan Sunnah Rasūl s.a.w. Dengan demikian, ia berarti telah mengamalkan amal shalih. Barang siapa mengingkari bepergian ini, berarti telah kafir dan diminta untuk bertobat, dan jika ia tobat maka ia dibiarkan, sedangkan jika tidak maka ia dibunuh.
Adapun orang yang meniatkan bepergian semata-mata karena ziarah kubur dan tidak meniatkan shalat di masjid, serta bepergian ke kota beliau dan tidak shalat di masjidnya, dan tidak memberikan salam kepada beliau dalam shalat, akan tetapi hanya mendatangi kuburan lalu setelah itu pulang, berarti ia telah melakukan bid‘ah yang sesat, bertentangan dengan Sunnah Rasūlullāh s.a.w. dan ijma‘ sahabat serta ulama umat.
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, yang pertama mengatakan haram, dan kedua, tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala.
Perbuatan yang ulama adalah ziarah syar‘iyyah, yaitu shalat di masjidnya dan memberikan salam kepada beliau ketika memasuki masjid dan ketika dalam shalat. Ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslim.
Hingga ia berkata: Aku mengingat bahwa dinyatakan mengucapkan salam kepada Nabi s.a.w. dan kepada kedua sahabat beliau. Pembahasan selesai.
Unduh Rujukan:
- [download id="14892"]
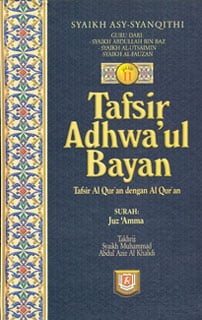
Komentar
Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?