هو
PASAL EMPAT
TAUḤĪD AŻ-ŻᾹT
(Bagian 4)
Maka, bagi seorang murid yang benar, wajib atasnya untuk membenarkan akan pengaruh atau kesan yang ditimbulkannya (āṡār), sehingga ia menjadi bersungguh-sungguh dan siap menerima tantangan apa pun dalam ijtihadnya. Karena sesungguhnya jalan yang akan dilaluinya itu amat sukar bagi jiwa (nafs). Kesukaran atau keadaan apa pun dalam ilmu żauq ini tidak dapat dilukiskan melalui tulisan (saṭr). Karena itu barang siapa yang dengan entengnya mengatakan bahwa ia telah memperoleh ilmu sang ‘ārif tersebut diperoleh lewat lafal, qaul (kata-kata), dan ta‘bīr (interpretasi yang mengarah pada pemberlakuan hukum rasional), maka sesungguhnya ia telah menjadi Kafir Zindiq. Na‘ūż bi Allāh min żālik.
Manakala pembukaan rahasia-Diri (tajallī) Allah dengan zat-Nya terjadi tanpa melalui perantara (wāsiṭah) pada seorang hamba yang dikehendaki-Nya, niscaya fanā’-lah diri orang ini di sisi-Nya. Ia menjadi “lenyap” dalam Allah, baik dari segi zat maupun sifatnya. Orang ini tentu saja mencapai tajallī tersebut karena kehendak-Nya juga, sebab tidak seorang pun yang mampu melakukannya secara sendirian tanpa kehendak-Nya, sekalipun misalnya ia telah melalui proses bimbingan dari syaikh-syaikhnya. Para syaikh ini hanya berperan sebagai penunjuk jalan dan tempat, sementara kondisi tajallī itu merupakan hal yang żauqī. Sehingga, jika seseorang tiada merasakan żauq, maka ia sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Hal ini seperti terungkap dalam pernyataan kaum bijak (hukamā’):
مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَدْرِ
“Barang siapa tiada merasakan zauq, ia tidak mendapatkannya (mengetahuinya – menggapai dengan pemahamannya).”
Pernyataan ini dapat diibaratkan dengan orang Jawi (istilah yang dipakai untuk menyebut Nusantara) yang berada di Jawi, yang dikhabarkan orang kepadanya mengenai rasa buah safar jal (sejenis buah-buahan yang umumnya tumbuh di dataran ‘Arab). Orang Jawa ini pasti tidak akan bisa merasakan rasa safar jal itu secara hakiki. Sebab, ia belum pernah merasakan secara langsung, sekalipun ada pelbagai cerita dari teman-temannya tentang rasa buah tersebut. Tetapi, jika ia sudah merasakannya secara langsung, barulah ia mengetahui rasa yang sesungguhnya atau yang hakiki dari buah safar jal tersebut. Demikian juga halnya dengan makrifat Allah. Jika seseorang telah merasakannya, niscaya hanya dirinya sajalah yang mengetahui rasanya, sehingga ia tidak merasa kesulitan untuk bercerita. Namun demikian, kaum ‘ārif sendiri yang telah mengalami hal żauqī tersebut, tidak dapat memberikan definisi dan isyarat yang persis mengenai hal ini. Mereka pada dasarnya lemah untuk memberikan semacam iktibar untuk masalah ini, dan bahkan menyadari akan keterbatasan makrifat mereka. Hal ini terlihat dari pengakuan sabda Nabi s.a.w.:
سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ
“Mahasuci Engkau ya Allah, kami tidak mengenal-Mu dengan sebenar-benar makrifat.”
Kaum ‘ārif merasa lidah mereka kelu untuk mengatakan perihal makrifat tersebut, sebagaimana sabda s.a.w.:
مَنْ عَرَفَ اللهَ كَلَّ لِسَانُهُ
“Barang siapa yang mengenal Allah, niscaya kelu lidahnya.”
Kekeluan lidah ini disebabkan oleh karena masalah ini merupakan masalah żauq (amr żauqī).
Adapun pemaknaan terhadap kalimat yang mengatakan bahwa “Allah Ada pada materi yang berwujud” adalah harus dalam konteks Hakikat dan Sifat Berdiri-Sendiri (Qayyūm)-Nya. Jika anda benar-benar mengenal-Nya, pemaknaan kalimat tersebut tidaklah harus bergulir pada konteks ittiḥād ataupun ḥulūl. Jika memang dikhawatirkan, maka melalui syuhūd, anda harus menyadarkan diri anda bahwa batas maksimal yang mungkin bisa anda capai dalam proses menuju kepada-Nya adalah hanya sampai pada Maqam Tauḥīd aṣ-Ṣifat. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan di antara para wali Allah memang hanya sampai pada maqam ini, mereka tidak memaksakan diri untuk sampai kepada Maqam Tauḥīd aż-Żāt. Sebagaimana telah disebutkan di awal pasal IV ini, mereka yang berhasil memperoleh Maqam Tauḥīd aż-Żāt tersebut hanyalah Rasūlullāh s.a.w. dan orang-orang yang – mungkin berada satu tingkat – di bawah qadam Rasūlullāh s.a.w.
Namun demikian, merupakan hak seorang hamba mana pun untuk mencapai Maqam Tauḥīd aż-Żāt tersebut. Seseorang yang merasakan tajallī Zat, niscaya ia akan lenyap di dalam laut Aḥadiyyah Wujud Mutlak, yang laisa kamiṡlihi syai’ (tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya). Ia tidak memperdulikan lagi bilangan amal yang disandarkan padanya dan juga pada makhluk lainnya, tidak menyamakan seseorang pun dengan dirinya, dan tidak condong kepada anggapan orang bahwa ia banyak berbuat amal kebajikan. Orang ini juga tidak akan berpaling dari suatu maqam ke maqam lainnya, yang terlepas dari ijtihadnya. Kecuali jika orang ini, yang tentu saja masih dalam rangkaian proses ijtihadnya, mengalami suatu sebab yang mengharuskannya berpindah kepada maqam tertentu. Sebab, maqam seperti ini, pencapaiannya bersifat gaib, akibat Wujud Mutlak Yang mengadakannya. Dia bahkan tidak mengetahui mengapa dia bisa mencapai maqam seperti itu.
Orang yang telah mencapai maqam tajallī Zat ini tidak akan merasakan lagi sesuatu pun lantaran tajallī Zat telah mengakhiri segalanya, semata-mata terfokus pada penyaksiannya terhadap Wujud al-Ḥaqq Yang Esa. Oleh karena itulah, akal orang ini tidak menyisakan tempat bagi pikiran-pikiran yang lain, dan hanya terbang dengan tajallī Nur akibat Yang Disaksikan. Syaikhunā al-‘Ᾱrif bi Allāh Maulānā asy-Syaikh Ṣiddīq Ibn ‘Umar Khān q.s. berpendapat:
“Barang siapa yang berada di Maqam (Tauḥīd aż-Żāt) ini, ia hampir-hampir tidak berpegang pada syari‘ah dan bahkan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh para ulama syari‘ah, sehingga ulama-ulama syari‘ah ini memvonisnya sebagai Zindik lantaran orang ini, yakni orang yang mempunyai hakikat, tidak menerapkan syari‘ah yang nyata.”
Inilah yang dimaksudkan oleh Imām al-Junaid r.a. sebagai berikut:
لاَ يَبْلُغُ أَحَدٌ دَرَجَةَ الْحَقِيْقَةِ حَتَّى يَشْهَدَ فِيْهِ أَلْفُ صِدِّيْقٍ بِأَنَّهُ زِنْدِيْقٌ
“Seseorang tidak akan sampai kepada derajat hakikat kalau belum dianggap Zindik oleh seribu orang ṣiddīq.”
Syaikh ‘Abd al-Wahhāb asy-Sya‘rānī r.h., bertanya kepada syaikhnya, Sayyidī ‘Alā al-Khawwāṣ q.s.: “Apakah derajat hakikat itu?” Syaikhnya menjawab:
“Derajat hakikat itu adalah hilangnya segala wujud yang tampak (ẓahir) ini dari pandangan, tapi bukan hilang dari nafs al-amr. Jadi, andaikata seseorang memandang dengan musyāhadah, maka melalui hatinya, ia tidak melihat kecuali hanya Allah s.w.t. Bilamana ia tidak melihat lagi selain Allah, maka ia tidak menyadari lagi perihal apa yang diucapkannya. Kata-kata yang yang diucapkannya itu tidak terikat dengan kaedah syari‘ah yang eksoterik (ẓāhir). Akibatnya, orang-orang ṣiddīq tersebut tidak membenarkannya, melainkan hanya menganggapnya sebagai Zindik. Sebab, mereka menjaga otentisitas eksoterisme syarī‘ah Nabi kita Muḥammad s.a.w. Mereka khawatir kalau-kalau hal demikian akan diikuti oleh orang lain, sebagaimana misalnya yang terjadi pada diri al-Ḥallāj.”
Yang dimaksud dengan ṣiddīq di sini adalah orang yang menempuh jalan syari‘ah sesempurna mungkin. Syaikh ‘Abd al-Wahhāb asy-Sya‘rānī r.h., bertanya lagi kepada ustaznya tersebut: “Apakah para sālik itu memang harus betul-betul sampai kepada hakikat?” Syaikhnya kemudian menjawab:
“Betul, para sālik itu akan sampai pada hakikat. Ia akan dibimbing oleh Allah s.w.t. melalui perantara syekhnya agar dinding yang selama ini menutupinya dibuka. Setelah berhasil, ia akan kembali lagi pada tingkatan kehidupan biasa (derajat adab) sebagaimana yang dijalani sebelumnya sebagai sosok salaf yang saleh.”
Maka, apabila bagimu telah nyata, kendati hanya sekejap, perumpamaan rahasia mengenai Dia melalui musyahadah – yang kehadirannya bersifat kekal dan tidak diselingi dengan kelupaan, dan hanya dimiliki oleh pribadi-pribadi mulia semisal anbiya’ dan auliya’ yang sempurna – maka peliharalah ia dengan cara membentenginya. Dan jangan engkau ceritakan kepada orang lain, sebab yang demikian itu merupakan di antara hal yang diharamkan Allah. Allah memerintahkan untuk menutupi jangan sampai diketahui orang lain, sebagaimana hal ini juga berlaku bagi Nabi Muḥammad s.a.w., yang diekspresikan dari sabdanya:
وَ للهِ مَحَارِمُ فَلاَ تَهْتَكُوْهَا
“Dan bagi Allah itu ada beberapa rahasia yang diharamkan-Nya untuk menyatakannya, maka jangan kamu buka!”
Jadi, jika telah nyata bagi anda mengenai rahasia musyahadah itu dengan zauq anda, maka pelihara dan jagalah! Anda harus menunaikan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, termasuk dengan tidak menceritakan masalah tersebut kepada orang lain, supaya ia tetap bersemayam pada diri anda. Ini merupakan rahasia hati (sirr) yang amat mulia, karena itu, sembunyikan oleh anda mengenainya, lebih-lebih, dari orang yang bukan ahlinya, karena syara‘ datang dengan memerintahkan untuk menyembunyikannya. Secara luas tentang ini, akan diterangkan pada ahkir pembahasan.
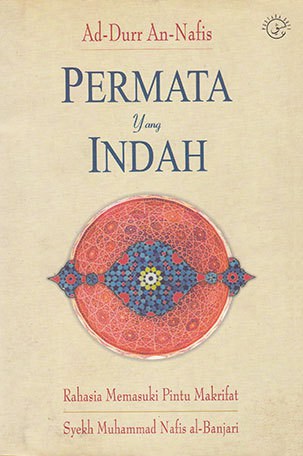
Komentar
Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?